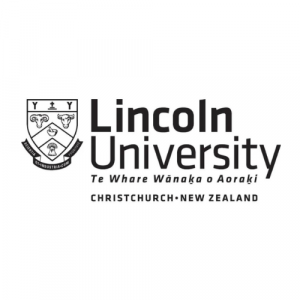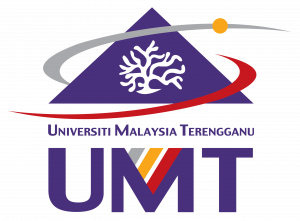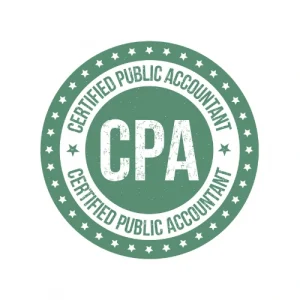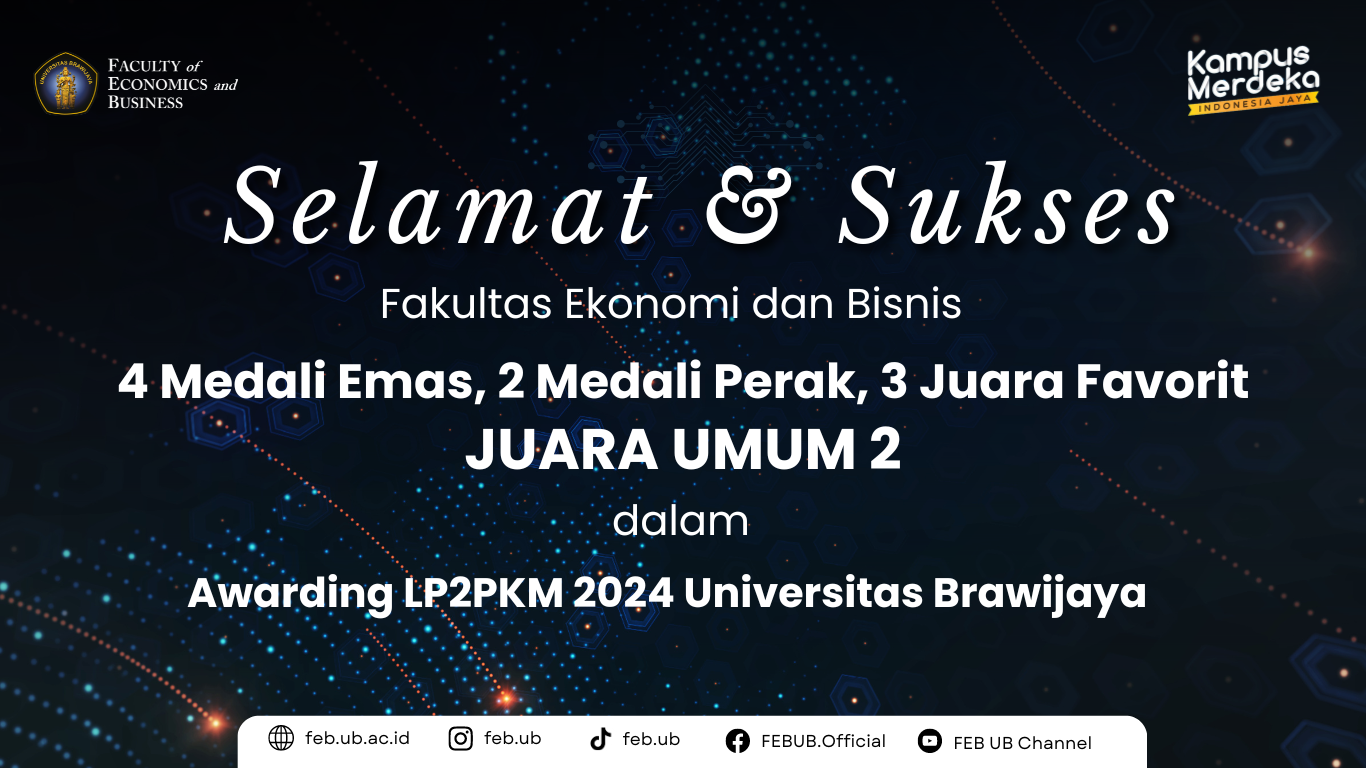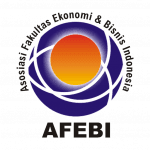PENGUMUMAN
- Semua Info
- Akademik
- Kemahasiswaan
- Umum & Keuangan
Berita & Informasi
Kami dengan senang hati mengumumkan kesempatan magang di KAP RSM Indonesia untuk periode 1 Mei – 31 Agustus 2024. Mahasiswa yang berminat diharapkan memenuhi persyaratan berikut: 👉Tidak sedang menjalani kuliah reguler atau magang lain. 👉 Bagi mahasiswa yang sedang menempuh skripsi, ujian/sidang skripsi dijadwalkan setelah masa magang berakhir. 👉 Magang akan diakui sebagai bagian dari […]
Pada Rabu, 17 April 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menggelar acara Penjurian dan Presentasi Proposal Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen, dan Keuangan (KBMK) tahun 2024. Kegiatan ini dimulai dengan Sambutan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa, Dr. Hendi Subandi, SE., MA., Ak., CA., IIAP, yang memberikan motivasi kepada […]
Kemitraan & Kerjasama