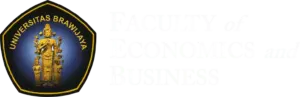Isu Transformasi Ekonomi Indonesia menjadi topik utama dalam kegiatan yang menghadirkan tiga narasumber dari berbagai bidang ekonomi dan kebijakan publik. Melalui pemaparan yang komprehensif, para narasumber menyoroti perubahan besar dalam struktur ekonomi nasional, tantangan deindustrialisasi dini, serta urgensi hilirisasi sebagai strategi kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, narasumber pertama menjelaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan dari sektor primer ke sektor industri dan jasa. Kontribusi sektor pertanian kini hanya sekitar 12,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun masih menyerap hampir sepertiga tenaga kerja nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan produktivitas yang tinggi antar sektor. Indonesia juga dihadapkan pada fenomena “deindustrialisasi dini”, di mana kontribusi sektor manufaktur menurun sebelum mencapai tingkat produktivitas optimal.
Sementara itu, narasumber kedua menyoroti kebijakan hilirisasi industri sebagai langkah strategis dalam memperkuat basis ekonomi nasional. Investasi besar-besaran di sektor hilir, terutama pada komoditas nikel dan besi-baja, telah mengubah struktur ekspor Indonesia secara drastis. Indonesia kini tercatat sebagai salah satu eksportir stainless steel terbesar di dunia. Namun, capaian tersebut diiringi dengan sejumlah tantangan, seperti gugatan World Trade Organization (WTO) terhadap larangan ekspor bijih nikel, risiko oversupply akibat ekspansi smelter yang berlebihan, serta isu keberlanjutan lingkungan dan transfer teknologi.
Narasumber menekankan bahwa kebijakan hilirisasi tidak boleh berhenti pada peningkatan nilai ekonomi semata, tetapi juga harus memperluas kesempatan kerja formal, memperkuat kapasitas industri lokal, dan menjaga keseimbangan ekologis. Dengan demikian, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan berkelanjutan.
Adapun narasumber ketiga memaparkan pentingnya integrasi antara hilirisasi industri dan perdagangan global sebagai mesin ganda pertumbuhan ekonomi berkualitas. Hilirisasi memperkuat sisi penawaran melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah, sementara perdagangan memperluas sisi permintaan lewat akses pasar dan efisiensi rantai pasok. Strategi ini perlu didukung oleh kebijakan yang targeted, time-bound, dan evaluated, agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.
Selain itu, pemberdayaan UMKM, pelatihan vokasional, serta pembangunan klaster industri di luar Pulau Jawa menjadi langkah krusial untuk menciptakan pemerataan ekonomi nasional. Narasumber juga menjelaskan bahwa transformasi ekonomi pada dasarnya merupakan perubahan orientasi dari sektor primer menuju sektor industri, di mana perdagangan berperan sebagai katalis utama proses tersebut.
Dalam kesimpulannya, pembicara menegaskan bahwa transformasi ekonomi Indonesia bertumpu pada dua sayap utama, yakni industrialisasi dan hilirisasi. Industrialisasi berfokus pada penggabungan sumber daya alam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kapabilitas industri nasional—contohnya melalui pembangunan smelter nikel modern di kawasan timur Indonesia. Sementara hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam serta penyerapan tenaga kerja.
Meski demikian, masih terdapat berbagai tantangan implementasi, seperti ketimpangan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, regulasi lintas sektor yang belum sinkron, serta risiko pendanaan dan investasi. Namun, dengan kebijakan yang terarah dan kolaborasi lintas sektor, hilirisasi diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan volume ekspor, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta pertumbuhan ekonomi nasional.